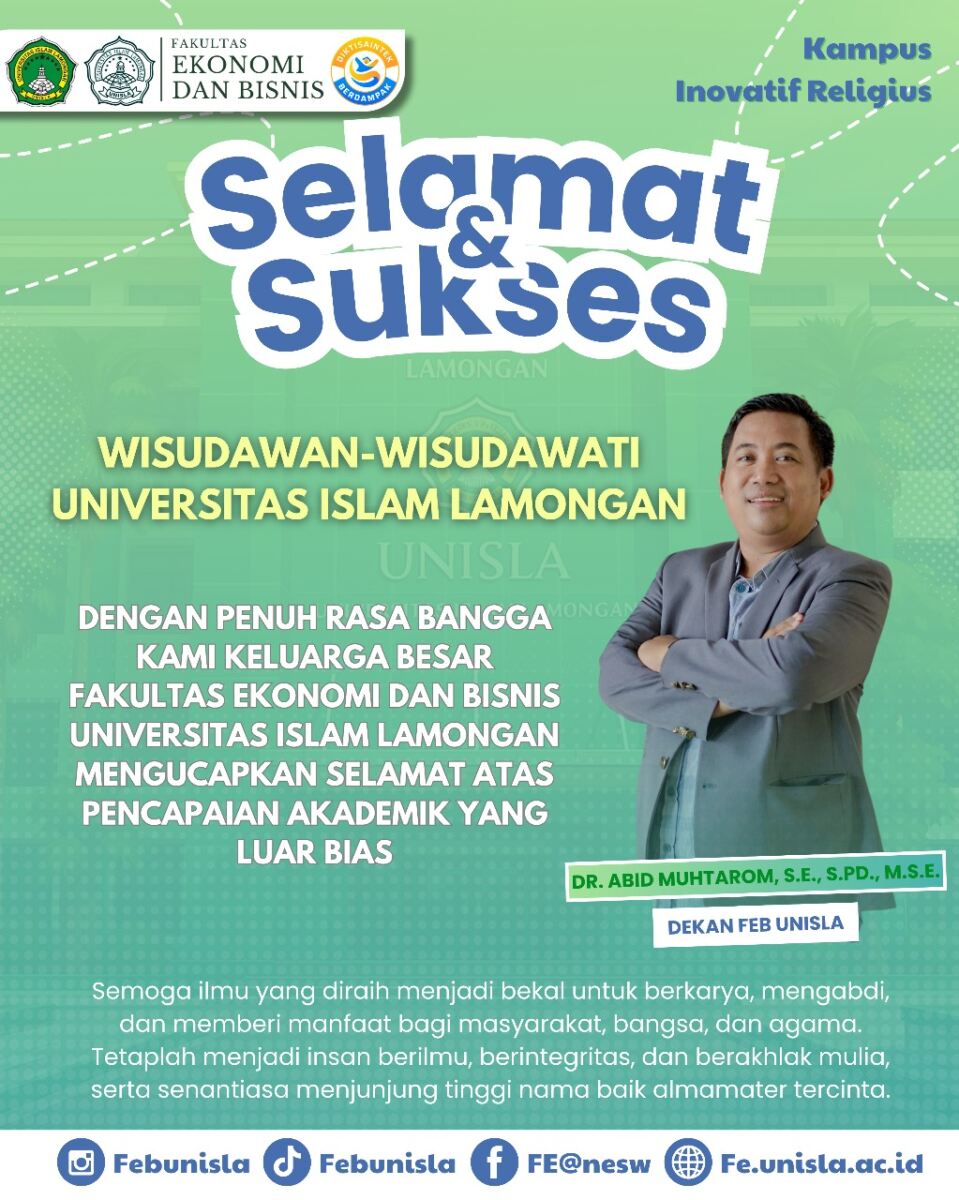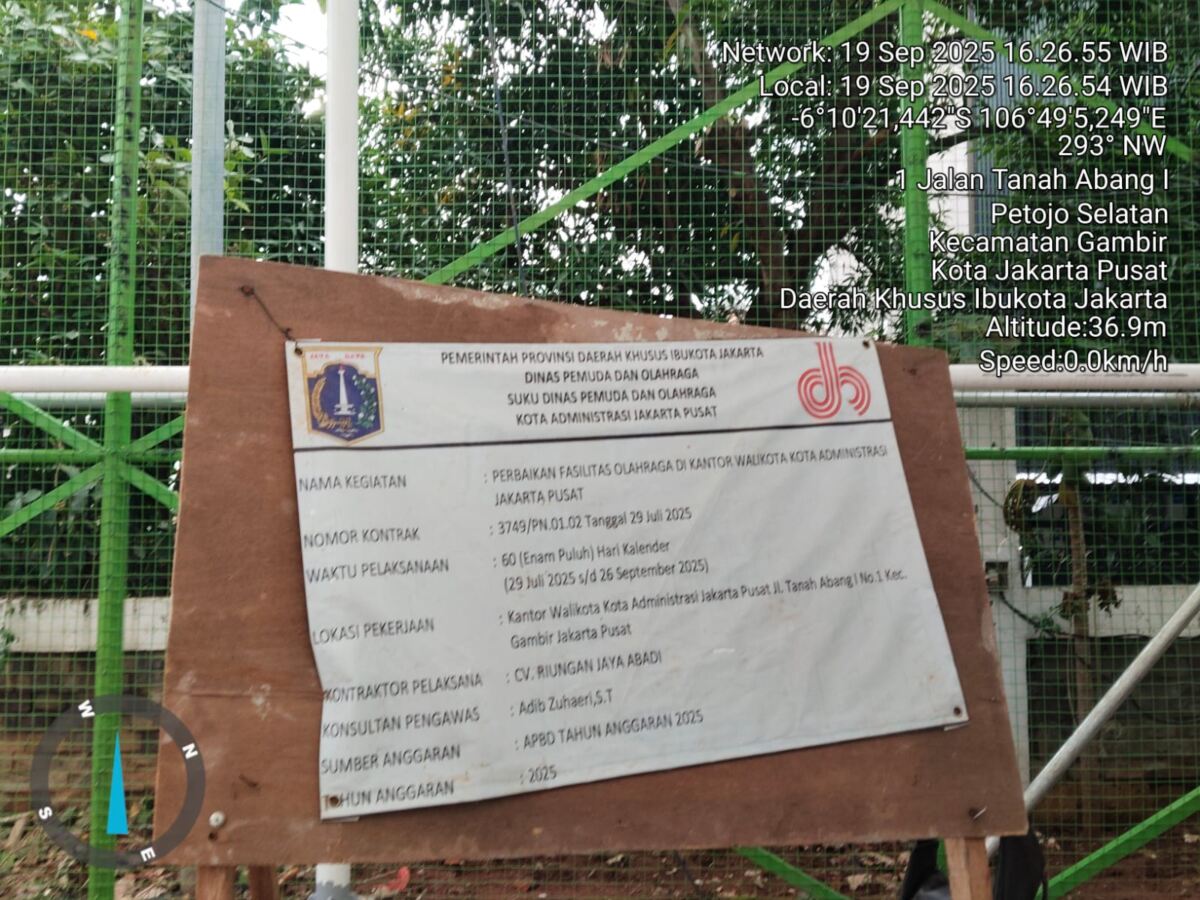Oleh: Dr. H. Abid Muhtarom, SE., MSE (Dekan FEB Unisla)
Lamongan, KabarOne News.com-Keputusan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menggeser dana jumbo sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke Bank Himbaran (BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan bank-bank negara lainnya) tentu menimbulkan perdebatan publik. Langkah ini secara resmi disebut sebagai stimulus likuiditas, dengan harapan mampu menambah ketersediaan dana murah di perbankan nasional agar kredit ke masyarakat dan sektor riil semakin lancar. Namun di balik optimisme tersebut, terselip sejumlah pertanyaan mendasar: apakah langkah ini benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, atau justru membuka celah baru bagi masalah moral hazard seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di masa lalu?
Pertama, mari kita lihat konteks positifnya. Pemindahan dana pemerintah ke bank-bank BUMN pada prinsipnya bertujuan agar likuiditas sistem keuangan lebih longgar. Likuiditas yang berlimpah akan menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank bisa menyalurkan kredit dengan bunga lebih rendah. Arah kredit bisa menyasar sektor-sektor produktif: UMKM yang menjadi tulang punggung lapangan kerja, sektor properti yang padat tenaga kerja, infrastruktur yang strategis, serta konsumsi rumah tangga yang menjadi motor 55% perekonomian Indonesia. Jika eksekusinya tepat, dana Rp200 triliun ini berpotensi menjadi “vitamin” kuat untuk mendorong pertumbuhan jangka pendek sekaligus menahan perlambatan global.
Kedua, kita tidak bisa menutup mata bahwa langkah ini memberi sentimen positif ke pasar keuangan. Kinerja perbankan BUMN kemungkinan membaik, karena ruang ekspansi kredit lebih besar dan pendapatan bunga bisa meningkat. Tak heran bila investor di pasar modal memberi respon positif; saham bank-bank besar akan terlihat lebih menarik. Dengan narasi tersebut, pemerintah bisa menampilkan langkah ini sebagai poster keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi.
Namun, seperti kebijakan fiskal dan moneter pada umumnya, selalu ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Risiko pertama adalah inflasi. Dengan menggelontorkan uang dalam jumlah sangat besar, otomatis uang beredar di masyarakat meningkat. Jika penyaluran kredit tidak dibarengi dengan produktivitas yang sepadan, konsekuensinya adalah kenaikan harga barang dan jasa. Daya beli masyarakat justru bisa tergerus. Bank Indonesia dalam hal ini akan bekerja lebih keras menjaga keseimbangan rupiah, stabilitas suku bunga, dan mengendalikan ekspektasi inflasi.
Risiko kedua adalah moral hazard. Sejarah mencatat bagaimana BLBI pada akhir 1990-an yang niat awalnya menolong perbankan justru berujung pada penyalahgunaan dana triliunan rupiah, yang hingga kini masih menyisakan luka hukum dan politik. Skema saat ini memang berbeda, karena penyaluran dilakukan melalui bank-bank BUMN yang relatif sehat dan diawasi ketat. Namun risiko penyalahgunaan tetap ada, terutama bila kredit digelontorkan ke sektor yang riskan, spekulatif, atau kurang terukur kelayakannya. Jika kredit tersebut macet, maka dana masyarakat yang seharusnya menjadi stimulus produktif justru berubah menjadi beban keuangan negara.
Risiko ketiga adalah efektivitas. Tidak sedikit bank yang justru enggan agresif menyalurkan kredit, meskipun sudah diberi tambahan likuiditas. Alasan klasiknya adalah kehati-hatian, risiko NPL (non-performing loan), atau permintaan kredit yang tidak memadai. Jika hal ini terjadi, Rp200 triliun tersebut hanya “parkir” di rekening bank tanpa multiplier effect ke sektor riil. Hasilnya, tidak ada dorongan signifikan ke ekonomi, sementara beban fiskal pemerintah tetap bertambah.
Dalam kerangka fiskal dan moneter, kebijakan ini bisa dipandang sebagai langkah berani tetapi penuh taruhan. Pemerintah membutuhkan instrumen cepat untuk menjaga momentum ekonomi, terutama saat tekanan eksternal meningkat, dari pelemahan global hingga gejolak harga komoditas. Namun di saat yang sama, Bank Indonesia harus ekstra hati-hati. Terlalu banyak likuiditas bisa membuat rupiah tertekan, inflasi meningkat, dan stabilitas makro terganggu.
Pertanyaan kritisnya kemudian: bagaimana agar kebijakan ini tidak bernasib sama seperti BLBI? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, transparansi dan akuntabilitas. Publik harus tahu dengan jelas ke mana saja kredit disalurkan, berapa besar porsinya untuk UMKM, sektor produktif, dan sektor konsumtif. Laporan ini sebaiknya dipublikasikan secara berkala agar pengawasan berjalan dua arah, dari regulator maupun masyarakat.
Kedua, seleksi sektor. Kredit harus diarahkan ke usaha-usaha yang benar-benar produktif dan mampu memberi nilai tambah, bukan ke sektor spekulatif semata. Misalnya, mendukung hilirisasi industri, pertanian modern, teknologi digital, energi terbarukan, dan sektor padat karya. Jika hanya terserap di sektor properti mewah atau konsumsi jangka pendek, manfaat jangka panjangnya akan minimal.
Ketiga, pengawasan ketat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan harus bekerja sinergis dalam mengawal aliran dana ini. Instrumen digital bisa dimanfaatkan untuk menelusuri arus dana, sehingga penyalahgunaan bisa diminimalisir sejak dini.
Keempat, keberpihakan kepada UMKM. Selama ini UMKM kerap kesulitan mengakses kredit karena dianggap berisiko tinggi. Padahal, mereka menyumbang 97% lapangan kerja dan 60% PDB. Dengan adanya dana segar, seharusnya bank BUMN didorong lebih berani menyalurkan kredit ke UMKM dengan skema penjaminan atau subsidi bunga dari pemerintah.
Pada akhirnya, Rp200 triliun ini bisa menjadi momentum besar sekaligus ujian besar. Jika tepat sasaran, dana ini akan memperkuat daya dorong ekonomi nasional, menjaga stabilitas sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun jika salah kelola, tidak menutup kemungkinan kita akan kembali menghadapi masalah klasik: kredit bermasalah, pemborosan fiskal, inflasi tinggi, hingga potensi kasus hukum yang mengingatkan kita pada BLBI.
Kita tentu berharap pemerintah belajar dari sejarah. BLBI menjadi pelajaran pahit bahwa niat baik tanpa tata kelola yang kuat bisa berbalik menjadi skandal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan Rp200 triliun ini bukan sekadar “menggelontorkan uang” melainkan benar-benar menggerakkan sektor riil.
Sebagai akademisi dan pengamat ekonomi, saya melihat kebijakan ini ibarat pisau bermata dua. Satu sisi bisa menjadi stimulus kuat, sisi lain bisa menimbulkan luka mendalam. Kuncinya adalah transparansi, keberanian, dan keberpihakan. Bila tiga hal ini dijaga, maka Rp200 triliun tersebut tidak akan tercatat dalam sejarah sebagai kasus baru ala BLBI, melainkan sebagai tonggak kebijakan strategis yang mengantarkan Indonesia menuju pertumbuhan berkelanjutan.
Namun, mari kita jujur pada diri sendiri: apakah eksekusi di lapangan akan seindah narasi di atas kertas? Inilah pertanyaan yang harus terus kita kawal bersama.